Analisa vegetasi adalah cara mempelajari
susunan (komposisi jenis) dan bentuk (struktur) vegetasi atau masyarakat
tumbuh-tumbuhan. Untuk suatu kondisi hutan yang luas, maka kegiatan
analisa vegetasi erat kaitannya dengan sampling, artinya kita cukup
menempatkan beberapa petak contoh untuk mewakili habitat tersebut. Dalam
sampling ini ada tiga hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah petak
contoh, cara peletakan petak contoh dan teknik analisa vegetasi yang
digunakan.
Prinsip penentuan ukuran petak adalah
petak harus cukup besar agar individu jenis yang ada dalam contoh dapat
mewakili komunitas, tetapi harus cukup kecil agar individu yang ada
dapat dipisahkan, dihitung dan diukur tanpa duplikasi atau pengabaian.
Karena titik berat analisa vegetasi terletak pada komposisi jenis dan
jika kita tidak bisa menentukan luas petak contoh yang kita anggap dapat
mewakili komunitas tersebut, maka dapat menggunakan teknik Kurva
Spesies Area (KSA). Dengan menggunakan kurva ini, maka dapat ditetapkan :
(1) luas minimum suatu petak yang dapat mewakili habitat yang akan
diukur, (2) jumlah minimal petak ukur agar hasilnya mewakili keadaan
tegakan atau panjang jalur yang mewakili jika menggunakan metode jalur.
Caranya adalah dengan mendaftarkan
jenis-jenis yang terdapat pada petak kecil, kemudian petak tersebut
diperbesar dua kali dan jenis-jenis yang ditemukan kembali didaftarkan.
Pekerjaan berhenti sampai dimana penambahan luas petak tidak menyebabkan
penambahan yang berarti pada banyaknya jenis. Luas minimun ini
ditetapkan dengan dasar jika penambahan luas petak tidak menyebabkan
kenaikan jumlah jenis lebih dari 5-10% (Oosting, 1958; Cain &
Castro, 1959). Untuk luas petak awal tergantung surveyor, bisa
menggunakan luas 1m x1m atau 2m x 2m atau 20m x 20m, karena yang penting
adalah konsistensi luas petak berikutnya yang merupakan dua kali luas
petak awal dan kemampuan pengerjaannya dilapangan. Untuk lebih jelas
bagan pekerjaan dapat dilihat pada gambar 1.
Sebagai contoh, hasil pengukuran KSA tumbuhan bawah dapat dilihat pada tabel 1. berikut ini :
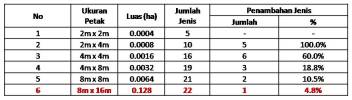
Dari
hasil diatas dapat dilihat bahwa penambahan jenis pada ukuran petak 8m x
16m sudah mencapai angka dibawah 5% (sesuai syarat Oosting, 1958; Cain
& Castro, 1959), maka dapat ditetapkan bahwa luas petak ukur yang
dapat mewakili komunitas pada rumput tersebut adalah adalah 8m x 16m
atau 0.128 ha. Luasan ini bukanlah harga mutlak bahwa luas petak ukur
yang harus kita gunakan adalah 0.128 ha, tapi nilai tersebut adalah
nilai minimum, artinya kita bisa menambah ukuran petak contoh atau
bahkan memodifikasinya karena yang harus kita perhatikan bahwa petak
contohnya tidak kurang dari hasil KSA. Contoh untuk memudahkan pekerjaan
dilapangan, sebaiknya ukuran petak tersebut berbentuk persegi, sehingga
petak hasil KSA tersebut dapat diubah menjadi ukuran 12m x12m.
Jika
sudah dapat ditentukan luas petak minimum, maka juga harus dapat
ditentukan jumlah petak contoh keseluruhan. Hitungann sederhananya,
tergantung kita menginginkan berapa luas total sampling yang kita
inginkan. Sebagai contoh luas kawasan yang akan kita eksplorasi adalah
10 ha, ukuran petak contoh yang ditentukan 12m x 12m dan kita
menginginkan intensitas sampling (IS) 5% (artinya, kita hanya akan
mengukur 1% dari luas total 10 ha). Maka jumlah petak contoh yang harus
kita gunakan adalah :
Dik : N = 10 ha
IS = 5% = 5% x 10ha = 0.5 ha
LPC = 12m x12m = 0.0144 ha
Ditanya : Jumlah petak contoh (n) ?
Jawab :
n = 0.5 ha / 0.0144 ha
n = 34.72
n = 35 petak
Hitungan
diatas adalah perhitungan sederhana tanpa mempertimbangkan tingkat
ketelitian dan tingkat eror pada pengambilan sampling.
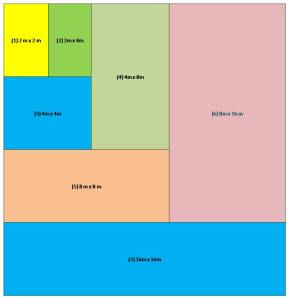
Gbr 1. Bentuk Pertambahan Petak Kurva Spesies Area
Cara peletakan petak contoh ada dua, yaitu cara acak (random sampling) dan cara sistematik (systematic sampling),
random samping hanya mungkin digunakan jika vegetasi homogen, misalnya
hutan tanaman atau padang rumput (artinya, kita bebas menempatkan petak
contoh dimana saja, karena peluang menemukan jenis bebeda tiap petak
contoh relatif kecil). Sedangkan untuk penelitian dianjurkan untuk
menggunakan sistematik sampling, karena lebih mudah dalam pelaksanaannya
dan data yang dihasilkan dapat bersifat representative. Bahkan dalam
keadaan tertentu, dapat digunakan purposive sampling.
Jika
berbicara mengenai vegetasi, kita tidak bisa terlepas dari komponen
penyusun vegetasi itu sendiri dan komponen tersebutlah yang menjadi
fokus dalam pengukuran vegetasi. Komponen tumbuh-tumbuhan penyusun suatu
vegetasi umumnya terdiri dari :
1. Belukar (Shrub) : Tumbuhan yang memiliki kayu yang cukup besar, dan memiliki tangkai yang terbagi menjadi banyak subtangkai.
2. Epifit (Epiphyte)
: Tumbuhan yang hidup dipermukaan tumbuhan lain (biasanya pohon dan
palma). Epifit mungkin hidup sebagai parasit atau hemi-parasit.
3. Paku-pakuan (Fern)
: Tumbuhan tanpa bunga atau tangkai, biasanya memiliki rhizoma seperti
akar dan berkayu, dimana pada rhizoma tersebut keluar tangkai daun.
4. Palma (Palm)
: Tumbuhan yang tangkainya menyerupai kayu, lurus dan biasanya tinggi;
tidak bercabang sampai daun pertama. Daun lebih panjang dari 1 meter dan
biasanya terbagi dalam banyak anak daun.
5. Pemanjat (Climber)
: Tumbuhan seperti kayu atau berumput yang tidak berdiri sendiri namun
merambat atau memanjat untuk penyokongnya seperti kayu atau belukar.
6. Terna (Herb)
: Tumbuhan yang merambat ditanah, namun tidak menyerupai rumput.
Daunnya tidak panjang dan lurus, biasanya memiliki bunga yang menyolok,
tingginya tidak lebih dari 2 meter dan memiliki tangkai lembut yang
kadang-kadang keras.
7. Pohon (Tree)
: Tumbuhan yang memiliki kayu besar, tinggi dan memiliki satu batang
atau tangkai utama dengan ukuran diameter lebih dari 20 cm.
Untuk tingkat pohon dapat dibagi lagi menurut tingkat permudaannya, yaitu :
a. Semai (Seedling) : Permudaan mulai dari kecambah sampai anakan kurang dari 1.5 m.
b. Pancang (Sapling) : Permudaan dengan tinggi 1.5 m sampai anakan berdiameter kurang dari 10 cm.
c. Tiang (Poles) : Pohon muda berdiameter 10 cm sampai kurang dari 20 cm.
Adapun parameter vegetasi yang diukur dilapangan secara langsung adalah :
1. 1. Nama jenis (lokal atau botanis)
2. 2. Jumlah individu setiap jenis untuk menghitung kerapatan
3. 3. Penutupan tajuk untuk mengetahui persentase penutupan vegetasi terhadap lahan
4. 4. Diameter batang untuk mengetahui luas bidang dasar dan berguna untuk menghitung volume pohon.
5. 5. Tinggi
pohon, baik tinggi total (TT) maupun tinggi bebas cabang (TBC), penting
untuk mengetahui stratifikasi dan bersama diameter batang dapat
diketahui ditaksir ukuran volume pohon.
Hasil
pengukuran lapangan dilakukan dianalisis data untuk mengetahui kondisi
kawasan yang diukur secara kuantitatif. Dibawah ini adalah beberapa
rumus yang penting diperhatikan dalam menghitung hasil analisa vegetasi,
yaitu :
a. Indeks Nilai Penting (INP)
Indeks
Nilai Penting (INP) ini digunakan untuk menetapkan dominasi suatu jenis
terhadap jenis lainnya atau dengan kata lain nilai penting
menggambarkan kedudukan ekologis suatu jenis dalam komunitas. Indeks
Nilai Penting dihitung berdasarkan penjumlahan nilai Kerapatan Relatif
(KR), Frekuensi Relatif (FR) dan Dominansi Relatif (DR),
(Mueller-Dombois dan ellenberg, 1974; Soerianegara dan Indrawan, 2005).
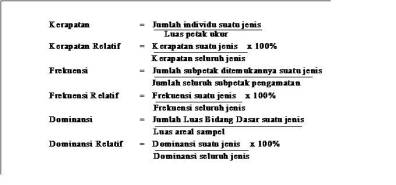
b. Keanekaragaman Jenis
Keanekaragaman
jenis adalah parameter yang sangat berguna untuk membandingkan dua
komunitas, terutama untuk mempelajari pengaruh gangguan biotik, untuk
mengetahui tingkatan suksesi atau kestabilan suatu komunitas.
Keanekaragaman jenis ditentukan dengan menggunakan rumus Indeks
Keanekaragaman Shannon-Wiener :
dimana : H’ = Indeks Keanekaragaman Shannon-Wiener
ni = Jumlah individu jenis ke-n
N = Total jumlah individu
a. Indeks Kekayaan Jenis dari Margallef (R1)
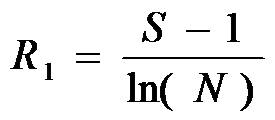
dimana :
R1 = Indeks kekayaan Margallef
S = Jumlah jenis
N = Total jumlah individu
a. Indeks Kemerataan Jenis
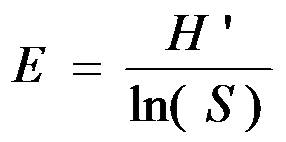
Dimana :
E = Indeks kemerataan jenis
H’ = Indeks keanekaragaman jenis
S = Jumlah jenis
Berdasarkan Magurran (1988) besaran R1 < 3.5 menunjukkan kekayaan jenis yang tergolong rendah, R1 = 3.5 – 5.0 menunjukkan kekayaan jenis tergolong sedang dan R1 tergolong tinggi jika > 5.0.
Besaran
H’ < 1.5 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong rendah, H’ = 1.5
– 3.5 menunjukkan keanekaragaman jenis tergolong sedang dan H’ > 3.5
menunjukkan keanekaragaman tergolong tinggi.
Besaran
E’ < 0.3 menunjukkan kemerataan jenis tergolong rendah, E’ = 0.3 –
0.6 kemerataan jenis tergolong sedang dan E’ > 0.6 maka kemerataaan
jenis tergolong tinggi.
a. Koefisien Kesamaan Komunitas
Untuk
mengetahui kesamaan relatif dari komposisi jenis dan struktur antara
dua tegakan yang dibandingkan dapat menggunakan rumus sebagai berikut
(Bray dan Curtis, 1957 dalam Soerianegara dan Indrawan, 2005) :
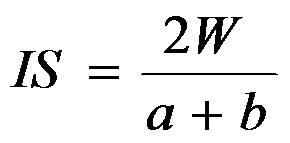
dimana :
IS = Koefisien masyarakat atau koefisien kesamaan komunitas
W = Jumlah nilai yang sama dan nilai terendah ( < ) dari jenis-jenis yang terdapat dalam dua tegakan yang dibandingkan
a, b = Jumlah nilai kuantitatif dari semua jenis yang terdapat pada tegakan pertama dan kedua
Nilai
koefisien kesamaan komunitas berkisar antara 0-100 %. Semakin mendekati
nilai 100%, keadaan tegakan yang dibandingkan mempunyai kesamaan yang
tinggi. Dari nilai kesamaan komunitas (IS) dapat ditentukan koefisien
ketidaksamaan komunitas (ID) yang besarnya 100 – IS. Untuk menghitung
IS, dapat digunakan nilai kerapatan, biomassa, penutupan tajuk atau INP.
Sebagai
contoh, kita membandingkan tingkat permudaan semai hutan primer dengan
hutan setelah ditebang dan dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :
Tabel 2. Nilai Kesamaan Kerapatan antara Hutan Primer dengan Hutan setelah ditebang pada tingkat Semai
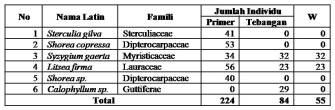
Maka nilai kesamaan komunitas (IS) = ((2 x 55) / (224 + 84)) x 100%
= 35.71%
Nilai
diatas menunjukkan bahwa antara kondisi primer dan setelah ditebang
dari segi jumlah individu (kerapatan) hanya mempunyai tingkat kesamaan
sekitar 35.71% artinya setelah dilakukan penebangan terjadi kehilangan
jumlah individu sekitar 64.29%.
f. Indeks Dominasi
Indeks
dominasi digunakan untuk mengetahui pemusatan dan penyebaran
jenis-jenis dominan. Jika dominasi lebih terkonsentrasi pada satu jenis,
nilai indeks dominasi akan meningkat dan sebaliknya jika beberapa jenis
mendominasi secara bersama-sama maka nilai indeks dominasi akan rendah.
Untuk menentukan nilai indeks dominasi digunakan rumus Simpson (1949)
dalam Misra (1973) sebagai berikut :
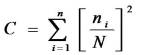
Dimana :
C : Indeks dominasi
ni : Nilai penting masing-masing jenis ke-n
N : Total nilai penting dari seluruh jenis
No comments:
Post a Comment